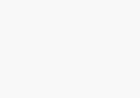Semangat Reformasi Gejayan

Fandis Nggarang
Gejayan tidak hanya sebuah ruang spasial (kawasan), tetapi representasi memori kolektif (peristiwa) yang ingin kembali dihadirkan dalam aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat di Jogja. Apa yang ingin dihadirkan adalah semangat reformasi yang pernah diperjuangkan di tahun 1998 melawan kediktatoran Soeharto. Perbedaannya adalah, Gejayan 20 tahun lalu adalah tonggak reformasi dan Gejayan tahun ini adalah koreksi atas reformasi yang sudah berusia dua dekade. Dari tulisan Romo Budi yang berjudul "Korupsi Nasional(isme), saya menyimpulkan turunnya mahasiswa ke jalan dipicu oleh adanya semacam memori atau bayangan bersama akan Indonesia yang mulai dari bahasa keresahan: apa yang terjadi bila RUU kontroversial tersebut diloloskan?"
R William Liddle dalam tulisannya di Kompas 19 Oktober 2019 yang berjudul "Empat Ancaman Demokrasi" menulis keberhasilan demokrasi di Indonesia bergantung pada penyelesaian masalah radikalisme, komunisme, separatisme, dan korupsi. Empat pokok persoalan ini merupakan hasil pengamatannya terhadap situasi pada tahun 1960-an. Komunisme tentu sudah menjadi ancaman yang hilang, ketika PKI sendiri sudah lenyap dan komunisme global menjadi ideologi yang usang. Walaupun kita sadari betul bahwa isu komunisme ini kerap dibangkitkan agar status quo penjaga negara - kelompok militer dan pemegang simbol agama - terus relevan dan dibutuhkan.
Yang tersisa secara nyata adalah isu separatisme, yang sekarang masih mengakar di Papua dan radikalisme yang membentang dari sikap intoleran hingga aksi terorisme. Persoalannya, nasionalisme, yang sangat diagung-agungkan di Indonesia ini, selalu menjadi benteng terhadap dua persoalan ini. Ini menjadi persoalan, ketika nasionalisme terbangun menjadi bubble wacana yang secara sepihak mulai menekan kelompok di Papua dan komunitas keagamaan tertentu yang memiliki pemahaman yang berbeda. Tentu, Pancasila dan NKRI adalah konsensus yang final, namun tidak dapat dipungkiri, kecendrungan untuk bersikap otoriter terhadap siapapun yang berbeda pandangan mulai menguat. Catatan kritis dalam konteks HAM bisa dijadikan acuan.
Karena Nasionalisme hanya diperbincangkan dalam konteks radikalisme ("Pancasila Sudah Final") dan separatisme ("NKRI Harga Mati"), publik mulai lupa bahwa masalah korupsi, yang diidentifikasi Liddle, adalah bentuk penyelewengan terhadap Nasionalisme itu sendiri. Romo Budi dalam tulisannya benar bahwa Korupsi, sebagai praktik yang mengabur-ngaburkan, mengkhianati imajinasi bersama masyarakat tentang Keindonesiaan. Maka muncul pertanyaan, apa yang mau kita definisikan tentang Indonesia ketika oligarki semakin menguat dan korupsi menjadi watak utamanya? Dengan demikian turunnya mahasiswa ke Jalan didorong oleh imajinasi bersama tentang Indonesia yang bersih.
Secara pribadi saya berpendapat bahwa Revisi UU KPK adalah sebuah keharusan, mengingat KPK sendiri sudah menjadi lembaga super body yang sangat politis. Namun, saya tetap berpikir positif tentang aksi turunnya mahasiswa ke jalanan, karena memang korupsi adalah masalah bersama yang harus disikapi "beyond" KPK secara sistemik. Namun, di tengah berjibunnya kata-kata yang muncul dalam demonstrasi, saya jadi berpikir bahwa apakah kata-kata demonstran masih memiliki kuasa? Di 1998, akumulasi rasa protes yang menguat selama 3 dekade mampu menghadirkan kata-kata yang membuat Soeharto turun dari kursi Presiden. Di tahun 2019 ini, seberapa besar kekuatan kata-kata, baik yang muncul secara eksplisit atau metafora?
Nasionalisme suku-bangsa Indonesia yang saling terpisah di jaman kolonial "terbayang" melalui bahasa dan pengalaman yang sama akan penindasan sebagaimana yang dijelaskan Benedict Anderson. Teknologi di masa lampau belum mampu menghubungkan manusia secara efektif dan efisien seperti yang dialami kita sekarang. Namun ketika teknologi pemersatu tersebut sudah mampu membangkitkan interaksi yang intensif di masa sekarang, apakah bahasa dan pengalaman kita memunculkan Nasionalisme yang semakin jelas? Dalam berjibunnya data, Nasionalisme hadir melalui ekspresi yang sifatnya euforia dan dalam rezim Informasi yang menuntut kejelasan, Nasionalisme jatuh dalam dogma kaku yang ritualis. Apakah ini dilema?
Ekspresi bahasa para mahasiswa yang direkam oleh tulisan Romo Budy kebanyakan mengandung metafora yang kuat. Namun, bahasa bukanlah 'alat' untuk mengekspresikan realitas semata, tetapi juga memiliki unsur pengikat. Sejauh mana kata-kata yang ditampakkan benar-benar diresapi dan punya daya praksis? Dalam kontestasi politik lima tahunan, misalkan, mampukah kita menjadi elemen yang menolak penggunaan politik uang dan kampanye berbasis SARA untuk menghasilkan figur politik yang tepat? Dengan demikian, kekuatan kritis mahasiswa dalam konteks perlawanan terhadap budaya korupsi harus mengarah pada konsolidasi penguatan demokrasi itu sendiri. Dalam demokrasi itu lah Nasionalisme- sebagai proses imajinasi bersama-bisa ditempatkan.
Imajinasi bersama itu tentunya mensyaratkan adanya bahasa publik yang sama. Ignas Kleden dalam sebuah diskusi, di mana saya pernah nimbrung di dalamnya, berkata bahwa kita sebenarnya tidak memiliki ruang publik. Bagaimana kita bisa memiliki ruang publik, jika kita tidak mempunyai bahasa publik? Selama ini berbagai kelompok primordial memaksakan diri agar bahasanya dipakai dalam ruang bersama tersebut. Bagaimana bisa kita berimajinasi tentang Indonesia bila kita tidak memiliki bahasa publik yang sama dan egaliter? Bahasa Indonesia adalah bahasa bersama, tetapi penggunaannya dalam ruang publik, memiliki intensi yang berbeda-beda. Apalah arti bahasa sebagai struktur-bentuk bila ia kehilangan fungsi emansipasinya?
Tugas mahasiswa, melampaui Revisi UU KPK, adalah mendorong agar bahasa publik bisa menjadi instrumen diskursus kita. Bahasa publik dengan segala kekuatan salurannya harus dimunculkan oleh mahasiswa, baik melalui parlemen jalanan atau medium alternatif kritis. Sialnya, dalam demonstrasi mahasiswa kemarin, ada dua perbedaan besar yang bisa ditarik. Dari sekian banyak kebijakan yang diprotes, mahasiswa terbelah dalam menyikapi RUU PKS. Mahasiswa di Jogjakarta menuntut agar RUU ini disahkan, sedangkan sekelompok mahasiswa di Jakarta bungkam tentang RUU ini. Ada apa? Saya melihat, RUU PKS adalah titik terakhir yang bisa membelah kepentingan ideologis mahasiswa. Kesimpulan ini tentu masih terbuka dan bisa diperdebatkan.
Nasionalisme atau Indonesia macam apa yang mau dibayangkan oleh generasi kelahiran 2000-an saat ini di tengah lautan informasi? Reformasidikorupsi dalam titik tertentu tidak hanya memunculkan sikap kritis, tetapi juga distrust, yang mana sentimentalitas memainkan peranan yang lebih. Benar dan salah menjadi tidak relevan, karena yang dipentingkan adalah kekuatan bahasa yang memesona. Namun, distrust terhadap pemerintah adalah ekspresi yang wajar, mengingat kekecewaan terhadap agenda pemberantasan korupsi dan penuntasan kasus HAM menguat. Tetapi apakah sikap pemerintah harus dilihat melulu dari kaca mata konspiratif? Bolanya sekarang ada di pemerintah, mampukah kabinet sekarang merengkuh kepercayaan publik?
Korupsi Nasional(isme) tulisan Romo Budy menunjukkan bahwa korupsi adalah pembangkangan terhadap nasionalisme, produk imajinasi bersama. Korupsi membuat kedudukan masyarakat tidak seimbang, sehingga gambaran tentang Indonesia ke depannya hanya ditentukan oleh penguasa. Oleh karena itu, perlawanan mahasiswa, sebagai agen intelektual, tidak melulu sebatas perlawanan jalanan. Perlawanan tersebut harus terus diarahkan pada penguatan demokrasi melalui penciptaan diskursus kritis yang mengarah pada tataran praksis. Tanpa komitmen praksis, gejayan memanggil akan terus terjadi dalam beberapa tahun ke depan, mengevaluasi kembali mahasiswa yang sebelumnya turun ke jalan, karena tidak membawa perubahan apa-apa!
Bukankah itu yang kita kritik dari Fahri Hamzah, Adian Napitupulu, atau Desmond Mahesa? Korupsi Nasional(isme) adalah beyond KPK, karena korupsi adalah ekosistem di mana kita juga ada di dalamnya. Agak naif bila korupsi hanya dipandang dari kaca mata dikotomis, rakyat vs penguasa. Saya percaya bahwa kekuasaan, selain memusat, juga menyebar. Kita memiliki andil pada persoalan sebagai satu kesatuan ekosistem yang membentuk wajah perpolitikan sekarang, sekalipun dengan kadar yang berbeda. Maka, logisnya, kita juga memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan dengan berbagai cara. Tagar Gejayan Memanggil (#gejayanmemanggil) adalah contoh bagaimana kekuatan media sosial bisa memobilisasi protes massa.
Imajinasi tentang Indonesia yang "bersih" sudah terbentuk. So, what's next?