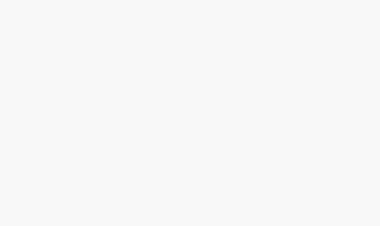KORUPSI NASIONAL(isme)

Budi Susanto S.J.
Lebih dari dua puluh tahun yang lalu, mengapa dan bagaimana peristiwa yang “terjadi” - atau lebih tepat “dijadikan” - oleh mahasiswa di Jogja, dalam bulan Mei 1998, boleh dinamakan sebagai gerakan Reformasi Nasional 1998. Seminggu menjelang 30 September 2019, lagi-lagi, mahasiswa (di) Jogja menjadi ingat untuk tidak melupa tentang kuasa kata dari suara atau bunyi “r-e-f-o-r-m-a-s-i” dari masa lalu di bulan Mei 1998. Itulah demonstrasi mahasiswa yang mashyur dinamai/kan “Gejayan Memanggil.” Menarik bahwa salah satu bahan untuk memperoleh kenang-kenangan tentang Reformasi Mei 1998 tersebut adalah penolakan mahasiswa terhadap RUU-KPK yang dibuat(buat?) oleh yang selama ini dikenal sebagai DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dari negara bangsa (nation state) RI yang berkantor di Senayan, Jakarta. Lokasi peristiwa kenangan - boleh juga disebut “ritus sosial” - dari Reformasi Jogja 1998 tersebut dipilih tidak di Alun-alun Utara seperti seperti pernah dicatat sejarah; tetapi dikenangkan di pertigaan, pertemuan antara Jalan Kolombo dengan Jalan Gejayan yang kini dinamai/kan Jalan Affandi. Seminggu kemudian, demonstrasi Gejayan Memanggil jilid II, jatuh persis pada tanggal 30 September 2019.
Salah satu peserta demo “Gejayan Memanggil” yang pertama - 23 September 2019 - menggunakan kaos yang menarik pandangan penulis. Pemuda pendemo itu mengenakan kaos dengan kata-kata di bagian punggungnya, berbunyi “Ini Tanah Airku, Di Sini Kita Bukan Turis.” Untaian kata-kata di punggung tersebut akan sangat mudah dipandang dan dibaca oleh orang yang ada di belakang pemuda tersebut; tentu saja tanpa sepengetahuan si pemilik kaos. Ternyata, kata-kata itu berasal dari salah satu puisi dengan pesan nasionalisme, hasil guratan Wiji Thukul. Pendemo itu juga menggunakan payung berwarna hitam.
Seorang pendemo lain - juga laki-laki - menggunakan jaket blue-jean yang bagian belakang ditempeli kertas putih dengan tulisan hitam sehingga mudah dipandang oleh penulis dari kejauhan, “Diperkosa Negara, Negara Dagelan.” Tanpa kesulitan, penulis dapat sekilas memandang - dan membaca - kata-kata yang tersurat pada “grafiti” di jaket itu. Apa yang tersirat dari kata-kata tersebut, nampaknya, berhubungan dengan tindak-tanduk pihak-pihak yang terkait(kaitkan) dengan urusan pemerkosaan dan lucu-lucuan (dagelan).
Inikah gambaran, keterbayangan, atau imajinasi dari nasionalisme di negara bangsa NKRI masa kini yang baru saja ber-HUT ke 74. Ingatan penulis ingin membuat kajian banding. Halaman sampul belakang edisi terbaru buku terlaris mendiang Benedict Anderson (1936-2015) berjudul Imagined Communities (IC), terbit perdana 1983, dan terbaru 2006; memuat pesan menarik. Dengan buku ini Benedict Anderson (selanjutnya BenA) mengajak pembaca untuk ikut menjawab pertanyaan mendasar berkaitan dengan apa yang disebut “nasionalisme.” Apa yang sesungguhnya membikin seorang warga negara rela hidup atau mati demi “nasionalisme.” Orang yang sama itupun bersedia memusuhi dan bahkan membunuh sesamanya (yang Lain) demi nasionalisme pilihannya itu. Menyempatkan diri membuat kajian banding dengan nasionalisme di Asia Tenggara (Spectre of Comparison, 1998), BenA perlu mengacu pada pendapat Lord Acton, tokoh politik Kerajaan Inggris, yang menganggap pada masa itu - paruh kedua abad 19 - ada tiga gerakan paling subversif yang mengancam Monarki Inggris. Gerakan nasionalisme adalah yang paling menarik rakyat, dan menjanjikan masa depan yang cerah. Dua yang lain yaitu gerakan egalitarianisme (mengancam aristocracy) dan komunisme (sebelum kena pengaruh Karl Marx) yang mempermasalahkan tentang prinsip hak milik pribadi. Tulisan ini pada dasarnya hanya singkat menggurat apa yang Ben Anderson pernah menyurat dalam beberapa buku dan artikel yang lain.
Hampir tiga perempat abad sejak bangsa Indonesia mendeklarasikan nasionalisme anti kolonial dan imperial (1945-2019), sebagian warga negara RI, mungkin juga para pembaca budiman, akhir-akhir ini sempat ikut(ikutan) khawatir, dan perlu sibuk mengikuti demo. Misalnya, mereka menganggap si/apa yang menjadi kekuatan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, berdiri sejak 2002) akan dilemahkan dengan RUU terkait yang baru. Penulis tidak melupa kata-kata BenA, segera sesudah terjadi peluang dan peristiwa “Reformasi Mei 1998". Saat itu BenA takut mengapa banyak WNI, khususnya Kelas Menengah, dan kaum elit Indonesia yang lebih cenderung mempermasalahkan dan menuntut kembalinya harta korupsi mantan presiden RI, Jenderal Besar Suharto. Perlu diketahui, karena karir akademisnya, BenA sempat dicekal selama 27 tahun (1972 - 1999) oleh rezim Orde Baru untuk masuk Indonesia.
Meskipun begitu, BenA menegaskan bahwa sementara saat rezim itu tergusur dalam “Tragedi Mei 1998" - entah kapan akan bangkit lagi - kalangan tertentu WNI itu terlalu mengutamakan hal untuk menuntut pengembalian uang hasil korupsi termaksud; daripada melihat kesempatan itu sebagai peluang memajukan demokratisasi. BenA merasa bahwa hal membesar-besarkan masalah korupsi adalah - seakan - menganggap harta dan uang hasil korupsi itu berasal-usul dari saku kantong nenek-moyang mereka. BenA yang paham sejarah peristiwa “Revoloesi Pemoeda” (1945-1949) mengingatkan bahwa masih ada banyak usaha, aksi dan gerakan untuk “mereformasi” dan memajukan demokratisasi dengan memperkembangkan nasionalisme seturut kemajemukan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan negara bangsa Indonesia.
Memang, tidak terlalu mudah dan sederhana untuk memahami gagasan BenA yang mengatakan bahwa “nasionalisme adalah gagasan tentang komunitas ter/di-bayangkan (imagined communities); di mana warga suatu negara bangsa terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan tak mampu mengenal sebagian besar warga yang lain, tidak bertatap muka dengan mereka, dan bahkan mungkin tak pernah mendengar tentang mereka. Namun toh di benak setiap orang yang menjadi warga bagsa itu hidup sebuah keterbayangan (imajinasi) tentang kebersamaan mereka” (Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. h.8).
Mengikuti gagasan BenA, tanpa memperkembangkan aksi, gerakan, atau peristiwa nasionalisme sebagai pilihan dasar yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan, akan menjadi lebih sulit untuk menghadirkan komunitas-komunitas terbayangkan demi mudah melupa bahwa melakukan korupsi adalah abai terhadap nilai-nilai tanpa pamrih dan mandiri yang diperlukan seorang patriot. Seorang WNI patriot yang memiliki negara bangsa, tanah air dan bukan sekedar seorang turis. Cukup jelas bahwa tindak korupsi terjadi akibat berbagai siasat pengabaian atau “penyamaran” - membuat samar-samar, buram, kabur - untuk menangkap dan menghayati “nasionalisme.” Dalam bahasa Jawa, hal yang samar-samar itu juga dapat nyamari (membahayakan, mengancam). Boleh jadi, juga, istilah bahasa Inggris “imagined” menjadi tidak mudah untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kata “imagined” cepat dianggap sama saja dengan kata “imajinasi, khayalan, bayangan, mimpi.”
Tiga tahun sesudah peristiwa tragedi Mei 1998 di Jakarta, BenA masih menulis (The Age, 12 Mei 2001) bahwa “masalah yang ada bukan hal kelangkaan demokrasi, tetapi tipisnya gagasan nasionalisme, terutama dalam kalangan orang kaya dan berpendidikan. Indonesia sesudah penggusuran kekuasaan rejim Orde Baru Mei 1998, membutuhkan seorang pemimpin yang jujur, tanpa pamrih. Seorang pemimpin patriotik yang, mandiri dan terbebas dari diskriminasi primordial kelas sosial, agama, dan ras/suku”.
Belum lagi, gara-gara pencekalan BenA selama 27 tahun, buku Imagined Communities (IC) tersebut baru dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia tahun 2001, selama 18 tahun sejak terbit pertama tahun 1983. Padahal, buku IC yang sudah dijual jutaan eksemplar secara global, sampai tahun 2006 sudah diterjemahkan dalam 29 bahasa nasional (baca: “bahasa ibu”), di 33 negara. Sejak awal dalam buku IC, BenA juga mensyaratkan bahwa imajinasi nasionalisme anti-kolonial hanya dapat efektif berbuah bila saja ada tiga pemangkiran dari: pertama: penggunaan bahasa keramat/suci (yang tidak sulit segera dianggap sama saja dengan kebenaran). Kedua, pemangkiran dari kepercayaan terhadap kuasa keilahian milik sebuah dinasti kekuasaan. Ketiga, pemangkiran dari campur aduk antara mitologi dengan sejarah ilmu pengetahuan tentang asal-mula alam semesta.
BenA juga memahami bahwa maju dan berkembangnya nasionalisme anti-kolonial sejak awal abad ke 20 di Hindia Belanda adalah karena dukungan media kapitalisme cetak (koran, majalah, cerpen, novel, dll.) berbahasa Indonesia - yang semula juga disebut bahasa Melayu Pasar. Berbahasa nasional Indonesia sebagai lingua franca demi nasionalisme dalam sebuah masyarakat plural Indonesia - dulu Hindia Belanda. Berbahasa Indonesia tidaklah sama dengan keadaan di negara Filipina yang menentukan mempunyai bahasa nasional Tagalog yang sebenarnya hanya salah satu bahasa ibu di pulau Luzon. James Siegel (Sadur, 2009), sejawat BenA di Universitas Cornell, mengatakan bahwa ada dua syarat dan kekuatan sebuah lingua franca dalam sebuah masyarakat plural yaitu: tidak menimbulkan rasa rikuh, dan juga tidak saling menyodorkan cermin di antara para penggunanya. Seorang WNI yang setia berbahasa nasional(isme) dan berhasil menemukan kenyamanan berimajinasi komunal tentang nasionalisme yang tanpa pamrih dan mandiri, semoga, tidak menjadi rawan dan rapuh di hadapan godaan kenikmatan korupsi. Tak mengherankan bahwa BenA juga dengan yakin berpendapat (Kuasa Kata, 2000, h.420) bahwa “Berbahasa Indonesialah yang menumbuhkan nasionalisme ketimbang nasionalisme yang menjadikan terbentuknya bahasa Indonesia.”
#Jogja. Tiga Hari Menjelang Pelantikan Presiden RI