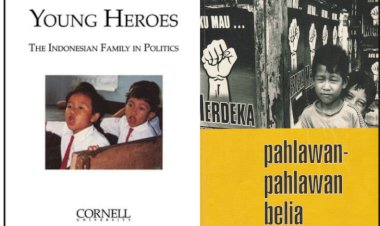Gejayan Memanggil “Jogja Slowdown”

|
|---|
Sesudah merayakan HUT penobatan beliau (7 Maret 1989-2020), dan menerima kunjungan persahabatan Raja Belanda, Willem (IV) Alexander di keraton Jogja (11 Maret 2020), Sultan Hamengku Buwana kesepuluh (HB X) berpidato mengenai wabah Covid-19. Dalam pidatonya berjudul Sapa Aruh (23 Maret 2020) tersebut, Sultan HBX tidak hanya memilih kata “Slow Down” dan bukan “Lock Down”; tetapi beliau juga cerdik mengingat-ingatkan pendengar - dan pembaca - tentang serat Kalatidha karya pujangga Jawa termasyhur, Ranggawarsita dari akhir abad 19 yang lalu.
Sejak pidato Sapa Aruh itu, banyak spanduk dipasang sebagai (re) aksi penduduk atau warga kampung, dukuh dan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menarik beberapa spanduk yang ditulis warga kampung atau dukuh Santren yang berada di sekitar jalan Gejayan - sekarang Jalan Affandi, Jogja. Spanduk ditulis kurang lebih dalam bahasa Indonesia. Warga wilayah dukuh atau kampung Santren memasang enam spanduk yang “berbunyi.”
(1) Perhatian Semua Tamu yang menginap
di wilayah RW 1 Santren Wajib Lapor pada Ketua RT/ RW
(2) Berhenti sebentar mohon untuk tutup mata
(3) Corona jahat, kayak mantan #Dirumah aja
(4) Jaga kesehatan, kamu belum nikah sama aku
(5) Corona Dilarang Masuk
(6) Maaf Jalan Ditutup. Ada Jatilan 24 Jam
Lokasi wilayah Santren ini - bersama Mrican, Demangan, Samirono Baru,dan Papringan - bertetangga dengan lima kampus besar di Jogja: UNY, UGM, USD, UAJY dan UIN Kalijaga. Penduduk, warga Santren dan kampung-kampung lain di sekitarnya - yang menampung mahasiswa kost - tidak (me)lupa tentang aksi-aksi protes, demo, dll. dari (mahasiswa) masa lalu, seperti: aksi Reformasi 1998 di Gejayan yang memakan korban Moses Gatotkaca, demo kaum muda milenial Gejayan Memanggil pada 23 dan 30 September 2019, dan unjuk-rasa “Gejayan Memanggil (lagi)” demi memprotes rancangan “Omnibus Law” pada awal tahun 2020 (lebih rinci tertuang dalam infografis )
Mungkin ada orang yang begitu saja menganggap bahwa suara-suara dari spanduk warga Santren - dan kampung atau desa lain di DIY - sekedar sama saja dengan kebiasaan “latah” yang ada dalam kebiasaan perilaku orang Jawa. Akan tetapi, nampaknya, untuk situasi masyarakat RI dan DIY masa kini yang sedang tertular pengaruh keranjingan “medsos,” menjadi lebih tepat kalau taburan spanduk-spanduk kerakyatan itu adalah (re) aksi dari pengalaman gelisah(!) mereka.
Peneliti masa Revoloesi Pemoeda (1942-1949), Benedict Anderson dengan cermat memahami pengalaman Perdana Menteri pertama RI, Sutan Syahrir (1909 - 1966) yang “gelisah” dalam masa perjuangan tahun-tahun awal kemerdekaan RI. Ben mencatat bahwa tahun 1945, dua bulan sesudah Pendudukan Jepang di Indonesia berakhir, sementara kolonialisme Belanda belum kembali mencengkeram kekuasaannya, Sutan Syahrir (Perdana Menteri pertama RI) menggambarkan kondisi saudara sebangsanya yang memulai revolusi ini dengan istilah gelisah. Ben menulis, “Inilah kata yang tidak mudah dicari padanannya dalam bahasa Inggris: makna semantiknya bisa meliputi anxious (cemas, trembling (gemetar), unmoored (tanpa pegangan), expectant (menanti-nanti).” (lihat: Benedict Anderson, 2015. Di Bawah Tiga Bendera, Anarkisme Global dan Imajinasi Antikolonial. Tangerang, CV Marjin Kiri. h.188). Menurut Ben, kalau diperbandingkan, itulah suasana yang sama - ada sesuatu yang “sedang menjelang,” yang “tidak pasti” - ketika pahlawan kemerdekaan Filipina (Jose Rizal) tanpa keraguan berjuang menyongsong dan memastikan kemerdekaan negaranya.
Spanduk warga Santren (yang gelisah) tersebut nampaknya adalah juga salah satu bentuk “gema” atau “gaung” - yang bertindak sebagai “kuasa kata” (Walter Benjamin, Illuminations 1955/1968) - untuk melanjutkan budaya revolusioner para pendiri negara bangsa RI - seperti Sutan Syahrir dan Bung Karno yang kelak mendapat julukan “Penyambung Lidah Rakyat.”
Harian Kompas (cetakan) menyempatkan diri ikut (ikutan) “menerjemahkan” dan menyebar-luaskan aksi-aksi berkaitan dengan Lock-down dan menulis spanduk sejenis yang ada di kampung Santren. Menarik juga sebenarnya untuk bertanya si/apa yang diharapkan oleh Kompas - dengan ratusan ribu tiras koran/perhari - membaca “kegelisahan” sejenis milik warga Santren, dan DIY pada umumnya.
Pada halaman pertama koran nasional Kompas cetak (4 April 2020), seorang wartawan foto koran tersebut disetujui redaksi untuk memuat foto kumpulan spanduk (berbahasa Jawa!):
Bar lelungan langsung adus, adus dewe opo adus ng sarjito
di rumah aja, kangen vid call)
C-19 Kapan koe lungo +62,
nglarani/ nyusahke / mateni aku dari virus, aku dengan yang serius
Terjemahan bahasa Indonesia:
Sesudah bepergian segera saja mandi, mandi sendiri atau (di)mandikan di (rumah sakit) Sarjito
Di rumah saja, kangen vid.call
C-19, kapan kau pergi dari +62
Bikin sakit/ susah/ bunuh aku dari virus, aku dengan yang serius
Perlu diketahui, tanggal 14 April 2020 presiden AS bernama Trump “tanpa pikir panjang” lagi menangguhkan pendanaan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pada hari yang sama, Sultan HB X juga mengeluarkan pidato wejangan Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi (mengasah ketajaman akal-budi dan membersihkan malapetaka bumi) berdasar ajaran Sultan Agung (1593-1645), leluhur kerajaan Mataram. Seminggu kemudian, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini (21 April 2020), pidato ketiga HBX berjudul Manekung, maneges Mring Gusti. Pada awal pidatonya, HBX sempat menulis “Saat ini juga mengingatkan saya ketika m e n g g a u n g k a n Maklumat Reformasi di hadapan ratusan ribu orang tahun 1998, bahwa kita akan bisa mengatasi masa krisis dengan baik.”
Menarik bahwa dalam tiga pidato tersebut, HBX waspada dan cerdik menggemakan peristiwa masa lalu kerajaan beliau untuk propinsi DIY masa kini. Dalam pidato Sapa Aruh, HBX menerjemahkan dan menggaungkan tembang (tulisan puitis) Pujangga Jawa Ranggawarsita (1802-1873) berjudul Kalatidha. Serat Kalatidha memaparkan bagaimana raja-raja Jawa pada akhir abad kesembilan belas (di bawah kolonialisme Kerajaan Belanda) sudah tidak lagi akrab, mengasah, dan memiliki “kuasa kata” dari akal-budi kejawen yang tajam. Kuasa kata-kata telah menjadi bahasa kosong sebagai kegemaran para penguasa sejaman.
Asal tidak melupa, dan cerdas memperhatikan catatan riset sejarah Takashi Shirasishi - tentang Aksi Bergerak revolusioner Haji Misbah pada dua dasawarsa awal abad ke20 di daerah Solo dan sekitarnya - pembaca budiman dapat memahami bagaimana rakyat kecil masa kini, langsung maupun tidak langsung, akan tidak mudah melupa (lewat beragam spanduk yang mereka tulis) tentang kuasa kata-kata dari masa lalu, dari warisan budaya leluhur mereka. Aksi bergerak dan berbagai spanduk tulisan warga Santren - dan penduduk DIY lainnya - nampaknya, dapat diterangkan dari sikap jeli (eling) dan cerdas (waspada) tentang “kehadiran” kuasa kata-kata: Kalatidha, ajaran Sultan Agung dan maklumat Reformasi Mei 1998. Nancy Florida, seorang ahli sastra klasik Jawa, mengungkap bahwa peran para pujangga Jawa adalah menulis pengalaman masa lalu demi melukis masa depan. Hal ini mengingat mereka adalah manusia mistik, utuh jasmani-rohani, yang mampu menjadi penyambung (lidah) suara rakyat (Menyurat yang Silam Menggurat yang Menjelang: Sejarah sebagai Nubuat di Jawa Masa Kolonial. Nancy K. Florida, 2003/1995. Jogja: Bentang Pustaka).
Bagi kalangan rakyat kecil dan para petani Jawa pada awal abad ke20 yang ketika itu mendengar kasak-kusuk politik, lalu pengalaman ikut pawai menghadiri “rapat raksasa” (diakrabi dengan istilah baru, modern, “vergadering” (bahasa Belanda) dan mendengarkan “voordracht” (pidato, ceramah) para pemimpin Serikat Islam yang sejajar dengan para pejabat Belanda - adalah pengalaman yang baru, luar biasa dan menggairahkan. Takashi menegaskan bahwa gerakan itu bukan karena rakyat kecil rela berduyun-duyun datang demi harapan-harapan Ratu Adil, “milenarian” dan “mesianik.” Tetapi, justru sebaliknya, pengalaman orang-orang pada saat menghadiri vergadering dan voordracht yang tidak lazim dan aneh itulah yang menggerakkan kuasa kata, bahasa terbayangkan(nya), sosok Ratu Adil (Takashi Shiraishi, 1997/1990. Zaman Bergerak. Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, h.89-90).
Bukankah taburan dan tebaran spanduk yang berangkat dari kegelisahan rakyat kecil adalah juga wujud sebuah gaung dari masa lalu demi segera bergerak dan berjuang melawan Covid19 masa kini?!
Jogja, pada HUT perayaan Hari Kartini 2020, Tim LSR
* * *
Sejak awal penularan wabah Covid19 di Indonesia (2 Maret 2020), berdasar sumber: www.covid19.go.id , pada tanggal 23 April 2020, jam 16:32. Jumlah orang terkonfirmasi: tertular 7,775 +357. Kasus. Dirawat 6,168, Meninggal 647, Sembuh 960. Positif COVID-19: DKI Jakarta (3,517), Jawa Barat (784), Jawa Timur (664), Jawa Tengah (538).
Data DIY dari sumber www.tribunjogja.com - Laporan Kurniatul Hidayah, Gaya Lufityanti (editor).
Konfirmasi kasus Covid-19 di DIY per 21 April 2020 adalah total PDP sebanyak 688 orang, 135 orang dirawat. Berdasarkan hasil lab, 72 orang dinyatakan positif (30 orang sembuh, 7 orang meninggal), 400 orang dinyatakan negatif; masih menunggu hasil lab sebanyak 216 orang (14 orang meninggal dunia).